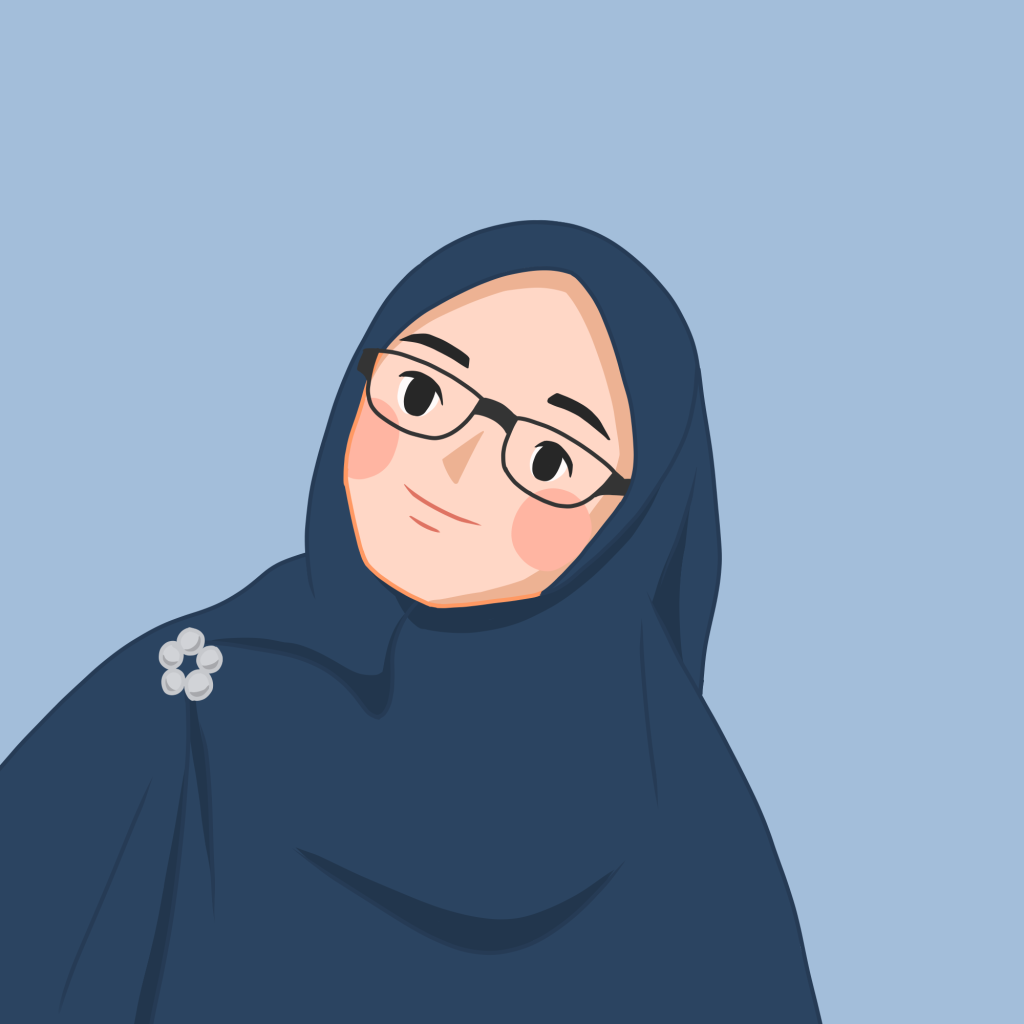“Apa kabar? Kamu bahagia?”
Setelah flashback beberapa kali, ternyata jawaban yang sering ku lontarkan atas pertanyaan sejenis itu lebih banyak menipu dari pada jawaban atas perasaan sebenarnya. Pasalnya, aku tak ingin orang lain tau soal ke-tak-bahagiaan-ku. Atau sekedar malas menjawab karena tahu si Penanya sebenarnya hanya basa-basi agar ada obrolan menyenangkan di awal perbincangan.
Siapa sih manusia lain yang sejujurnya mau mendengarkan cerita sedih atau kisah menyakitkan orang lain? Tentu tak banyak. Hanya orang-orang tulus yang benar-benar ingin mendengarkan apa yang terjadi pada diri kita, bukan sekedar mendengar saja.
——
Suatu ketika, tak lama setelah kematian Bapakku pun, ada seorang yang nyeletuk, “Kok kamu bisa tegar, gak nangis tersedu-sedu gitu pas Bapakmu meninggal?”
Di lain kesempatan, seorang yang ku percaya berkomentar dengan pelan, “Ini pertama kalinya saya lihat kamu nangis lo. Karena sehari-hari kamu kelihatannya ceria dan supel.”
Sesungguhnya ada yang agaknya kurang pas dari percakapan-percakapan itu. Banyak yang mengira senyum dan keceriaan di wajah itu selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan, begitu pula sebaliknya wajah yang muram dan datar berkaitan dengan perasaan tak menyenangkan lainnya. Padahal, dunia yang kita tempati ini tak sesederhana itu, begitu pun dengan manusia dan segala karakternya.
——
Sementara itu, banyak yang sering menggaung-gaungkan, “Setiap manusia berhak bahagia. Karena itu bahagia tidaknya, kita yang usahakan.”
Seolah-olah bahagia itu wajib dimiliki, meskipun yang digunakan pada kalimat di atas adalah kata hak. Tidak bahagia, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Tidak bahagia, berarti ada yang nggak pas sama jiwanya. Tidak bahagia, berarti terlalu banyak hal-hal negatif yang menutupi diri. Benarkah?
Bukankah berat jika harus pura-pura bahagia ketika sedang bersedih? Bukankah tak menyenangkan jika harus tertawa ketika diliputi amarah? Bukankah sulit untuk tersenyum ketika sedang gundah gulana?
Seperti baru-baru ini, aku mengalami pertentangan bathin karena melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan nurani. Sayangnya aku tak bisa berbuat apa-apa karena tak punya kuasa sama sekali. Benar, aku hanya sebagai tukang yang hanya bisa mengatakan “Siap” jika diperintahkan, tanpa bisa menentang sama sekali. Aku melakukan pekerjaan itu dengan hati yang penuh dengan emosi gelisah dan rasa tercekat.
Bukan sekali ini sebenarnya kejadian sejenis itu ku alami, sejak menjadi bagian dari abdi dalem. Anehnya, aku menangis setiap menjalani hal itu, sebagai bentuk dari mimpi buruk soal dosa jariyah yang berdampak pada banyak pihak ketidakberdayaanku. Rasa bersalah yang menyelimuti bathinku sebenarnya tak perlu ku dramatisir seperti yang dinasehatkan oleh beberapa orang sekitarku, “Dahlah, yang bertanggungjawab di akhirat kelak toh juga para pemimpin-pemimpin itu.”
Maka, haruskah aku tetap menunjukkan muka bahagia? Ya, tentu saja. Cerminan pelayan publik sayangnya harus pandai mengelola emosi, terutama setelahnya dituntut untuk tampil di layar kaca. Tak kan ada yang peduli pada segala jenis emosi atau semarah apapun diriku pada kebijakan, keputusan atau arahan yang amburadul sekalipun di dalamnya. Penonton lagi-lagi hanya melihat sebagai bagian dari pelayan publik.
——
Andai jenis perasaan dan emosi itu dijabarkan detail, tentu tidak hanya melulu soal bahagia. Sedih, bimbang, tiada rasa, kagum, sesal, marah, malu, bergairah, penasaran, khawatir, dan jenis emosi lainnya pun sama berharganya dengan bahagia. Tak ada yang setingkat lebih tinggi ataupun lebih rendah bukan? Atau memang ada manual book yang memberikan ranking atas jenis perasaan itu?
Di sisi lain, hidup sebagai orang dewasa ternyata benar-benar tak mudah. Ada otak yang mengatur berbagai jenis emosi agar yang tampak di muka berbeda dengan yang ada di hati. Hingga sampai pada ujung sebuah kesimpulan bahwa apapun emosi yang dirasakan, mau tidak mau kudu bahagia. Yang penting bahagia, cukup. Haruskah begitu?